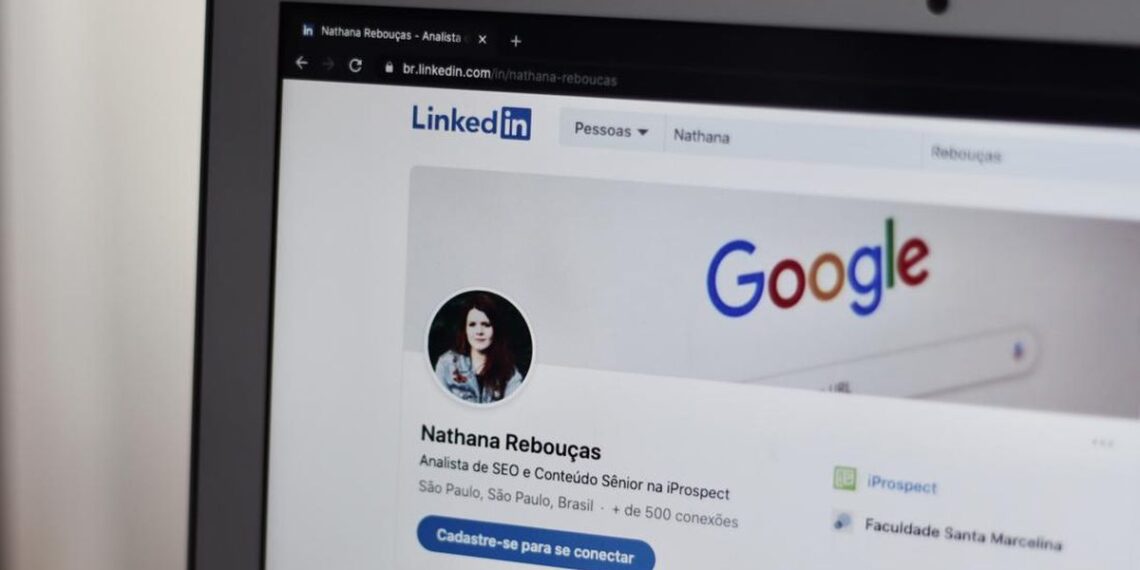Kanal24 — Sejak pertama kali diluncurkan pada 2003 oleh Reid Hoffman, LinkedIn menjelma sebagai ruang utama para profesional untuk membangun jejaring dan citra diri. Berbeda dengan Instagram, TikTok, atau X, LinkedIn menuntut penggunanya tampil dengan identitas asli. Foto formal, nama sungguhan, serta konten yang terkurasi seakan menjadi syarat tak tertulis agar seseorang dianggap “layak” berada di dalamnya.
Namun, di tengah arus formalitas itu, muncul fenomena baru. Beberapa unggahan kocak yang berawal dari keluh kesah Gen Z justru menjadi viral. Misalnya kalimat satir, “Semua gue lamaran. Apakah ada yang nyangkut? Enggak. Akhirnya? Nggak tahu. Ilang aja udah. Pesannya? Simpel aja nasi goreng satu, sedeng, telornya didadar.” Konten ringan semacam ini mendobrak pakem LinkedIn yang biasanya dipenuhi narasi prestasi cemerlang atau cerita karier yang dramatis. Fakta bahwa unggahan bernada humor mampu mencuri perhatian menandakan bahwa audiens di platform tersebut juga lelah dengan pencitraan berlebihan.
Baca juga:
Otrovert Kepribadian Baru di Luar Pola Umum
Antara Rayuan Prestasi dan Tekanan Sosial
LinkedIn awalnya dirancang sebagai ruang untuk memperluas relasi profesional. Namun, seiring berkembangnya fungsi, platform ini berubah menjadi panggung personal branding. Berbagi pencapaian, menulis opini, hingga memberi saran karier kini dianggap langkah strategis untuk menaikkan daya tawar diri di mata perusahaan maupun rekan kerja.
“Banyak orang lelah dengan sifat toksik di media sosial lain. LinkedIn seolah menawarkan alternatif yang lebih profesional,” ujar Jennifer Thompson, Digital Marketing Strategist, dalam sebuah tulisannya. Meski begitu, ada sisi gelap di balik maraknya tren personal branding. Tidak sedikit pengguna terjebak dalam pola baku: pencapaian harus gemilang, cerita wajib fantastis, dan ekspektasi melangit. Hasilnya, interaksi di LinkedIn kerap terasa artifisial. Komentar seragam seperti “very insightful” atau “thank you for sharing” membanjiri lini masa, bukan karena ketulusan, melainkan demi meningkatkan engagement semata.
Integritas yang Dipertaruhkan
Kasus Janney Hujic menjadi contoh nyata. Ia mengunggah foto bersama seseorang yang diklaim sebagai Piyush Gupta, mantan CEO DBS Bank, sembari menceritakan proyek besar pemberdayaan perempuan yang akan ia jalankan. Masalahnya, pria dalam foto itu ternyata bukanlah Piyush Gupta. Sang “aktor” bahkan mengaku sudah sejak awal memberi tahu Janney soal identitasnya.
Meski akhirnya Janney menyebut unggahan itu hanya “lelucon tidak berbahaya”, publik terlanjur menilainya sebagai upaya manipulatif. Brand Strategist Benjamin Loh berkomentar tegas: “Dengan fakta yang terang benderang, ia terus berbohong. Integritas kini dipertanyakan, atau jangan-jangan kita memang sudah terlalu berlebihan dalam membangun personal branding?” Kejadian ini menegaskan bahwa strategi branding tanpa kejujuran hanya menghasilkan kebalikannya yaitu hilangnya kepercayaan publik.
Kritik Terhadap Formula Seragam
Suara kritis juga datang dari penulis dan pengamat LinkedIn, Tim Denning. Ia menilai personal branding justru kehilangan makna ketika dilakukan secara massal dengan formula sama. “Ketika keegoisan diperlihatkan kepada publik umum, lalu jutaan orang melakukannya bersamaan, rasanya mengerikan,” katanya. Menurut Denning, obsesi terhadap citra membuat banyak orang gagal melihat dirinya secara jernih. Alih-alih menampilkan otentisitas, mereka terjebak dalam narasi klise yang diulang-ulang.
Angin Segar dari Generasi Muda
Di tengah atmosfer penuh polesan, konten-konten ringan ala Gen Z menjadi penyegar. Humor, keresahan, bahkan satire sederhana menunjukkan bahwa manusia tidak harus selalu sempurna di ruang profesional. Justru keotentikan itulah yang mampu menarik simpati audiens. Fenomena ini sekaligus mengingatkan bahwa personal branding seharusnya tidak menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Identitas profesional bisa dibangun tanpa kehilangan sisi manusiawi.
Strategi atau Ilusi?
Personal branding di LinkedIn memang bisa menjadi strategi penting untuk membuka peluang karier. Namun, ketika dilakukan dengan rumus baku prestasi menggunung, cerita bombastis, dan interaksi palsu—ia berubah menjadi ilusi. Kasus Janney dan kritik dari Denning menegaskan pentingnya integritas. Sementara, humor segar dari Gen Z membuktikan bahwa otentisitas tetap relevan, bahkan di ruang yang kerap dituduh terlalu formal.
Pada akhirnya, LinkedIn hanyalah medium. Yang menentukan nilai personal branding bukanlah seberapa indah narasi yang ditulis, melainkan sejauh mana ia mencerminkan realitas diri. Di era digital yang penuh distraksi, kejujuran bisa jadi strategi terbaik untuk membangun kepercayaan jangka panjang.(tia)