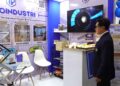Oleh Ria Casmi Arrsa
Dinamika dan perjuangan kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja dan akademisi yang menolak penetapan UU Cipta Kerja tidak pernah surut meskipun pada awalnya MK menetapkan UU tersebut inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat tersebut oleh berbagai kalangan dianggap sebagai putusan banci dan tidak tegas sehingga tidak bisa memberikan jaminan atas pemenuhan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun eskalasi kelompok yang menolak UU Cipta Kerja bisa bernafas sedikit lega dengan prediksi Presiden akan melakukan perubahan terhadap materi muatan UU Cipta Kerja dan apabila dalam waktu 2 (dua) tahun yang dipersyaratkan oleh Putusan MK tidak dipenuhi maka UU Cipta Kerja menjadi batal demi hukum termasuk isi batang tubuhnya.
Akan tetapi prediksi tersebut tidak terjadi, justru penulis melihat pada saat yang bersamaan Pemerintah sedang memainkan strategi untuk merespon Putusan MK tersebut secara simultan. Kondisi ini didiskripsikan seperti permainan roller coaster dalam berhukum yang justru memicu adrenalin dan kekuatan daya tahan untuk bertarung di area legislasi politik. Dinamika permainan roller coaster yang di sutradarai oleh Pemerintah pasca Putusan MK di bacakan yaitu (a) mengambil langkah untuk merevisi UU No 12 Tahun 2011 dengan memasukkan metode omnibus dan (b) melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan di dalam UU Cipta Kerja serta (c) melakukan konsolidasi politik di parlemen. Setelah babak ini diselesaikan selanjutnya Pemerintah mengambil langkah taktis untuk menetapkan Perpu sebagai strategi hukum untuk mempercepat penetapan UU Cipta Kerja yang secara teoritik Penetapan Perpu dipandang sebagai hak prerogatif Presiden yang secara bersamaan dalam ranah teoritik juga muncul istilah hak eksklusif Presiden.
Pasca Perpu tersebut ditetapkan menjadi UU No 6/2023 tentu dimensi hukum nasional menghadapi babak baru manakala pasca MK menyatakan penetapan Perpu Cipta Kerja konstitusional melalui Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023. Dalam Putusan tersebut dapat dipahami bahwa permohonan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. MK menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tentu saja saat merespon hal tersebut terbayang akan perdebatan kelompok yang memiliki segudang ilmu pengetahuan yang memandang bahwa secara prosedural due process of law dan substantive due process of law penetapan Perpu Cipta Kerja dipandang sebagai suatu pranata hukum yang inkonstitusional akan tetapi segenggam kekuasaan jauh lebih superioritas dan mendapatkan ruang justifikasi peradilan bahwa perumusan dan proses nya telah memenuhi kaidah dan/atau prinsip-prinsip konstitusi. Menarik untuk mencermati pandangan yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej yang mengutip pendapat sang begawan ilmu hukum progresif Satjipto Rahardjo bahwa dalam dimensi hukum modern kita akan melihat kenyataan bahwa dalam aspek penegakan hukum (law enforcement) tidak selamanya dalam berhukum pihak yang benar akan menang dan yang salah akan kalah karena hukum itu merupakan seni berintepretasi (the art of the intepretation). Meskipun Putusan hakim dipandang tidak bisa memenuhi rasa keadilan dan rancu dalam pertimbangannya tetap saja Putusan tersebut final dan mengikat dan menuntut i’tikad baik oleh siapa saja untuk mematuhi dan mentaatinya.
Dalam situasi tersebut apa yang harus dilakukan, memilih untuk tidak mematuhi, membangun daya tawar politik melalui Pemilu atau bahkan membangun gerakan melalui skema pembangkangan masyarakat sipil (civil disobedience) sangat memungkinkan akan tetapi terlalu spekulatif dan banyak pertumpahan darah yang akan dihasilkan. Sementara tuntutan dinamika masyarakat akan keadilan, kemanfaatan dan kepastian menjadi tujuan atau cita hukum itu sendiri terus berkembang. Oleh karena itu membangun kesiapan pranata hukum dalam konteks pelaksanaannya menjadi kunci keberlanjutan sistem hukum yang berlaku. Mengutip padangan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch meskipun penulis agak memaksakan pandangannya karena pada akhirnya otoritas negara yang memiliki kekuatan dan keuasaan untuk menentukan keabsahan dan melaksanakan hukum pasti akan melahirkan berbagai kebijakan turunannya yang bisa saja pro terhadap keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat yang bisa juga tidak mereprentasikan keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat. Maka dari itu di dalam dalilnya Radbruch mengemukakan bahwa jika keadilan bentrok dengan kepastian hukum maka eksistensi hukum itu mungkin tetap sah (dan dapat digunakan) kendati hukum itu menjadi hukum yang buruk karena dianggap gagal mencapai tujuannya yang sarat dengan pertentangan nilai. Akan tetapi pada satu titik apabila dalam pelaksanaannya terdapat konflik yang tidak lagi dapat ditoleransi sehingga hukum itu tidak saja buruk akan tetapi sudah cacat maka keadilanlah yang harus diutamakan dan meninggalkan hukum yang cacat (unrichteges recht) itu. Setidaknya refleksi tersebut menjadi alasan bagi kita untuk mengontrol tegaknya dimensi negara hukum Indonesia.
Penulis adalah Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah/PPOTODA dan Dosen Hukum Tata Negara FH-UB